“Aku gak biasa meminta sih. Masa untuk beli bedak aja aku harus minta ke suamiku..”
Siang itu adalah siang yang panas, ditambah dengan keriuhan khas kantin sekolah, disanalah aku dan dua orang teman sedang mengisi waktu sambil menunggu anak-anak kami pulang sekolah.
“Mungkin kamu gak risih untuk melakukan itu,Va. Tapi sejak kuliah aku sudah mandiri. Uang kuliah kucari sendiri tanpa minta orang tua lagi. Mungkin karena itu aku sekarang memutuskan bekerja juga..”
Kupandangi lagi wajah itu. Yah, baru sekitar setengah jam ini kami mengobrol akrab. Biasanya kami hanya bertukar senyum layaknya dua ibu yang kebetulan saling berpapasan. Hari ini adalah hari pertama masuk sekolah pasca liburan panjang Lebaran. Buat kami, para ibu yang biasa mengantar dan menunggui anak di sekolah, rutinitas ini membuat kami sering bertemu. Tapi lain halnya dengan hari ini, bermunculan-lah muka-muka “baru” yang biasanya hanya muncul ketika penerimaan raport. Pertemuan dengan dua teman ngobrolku kali ini juga dimulai dengan sapaan saling bertukar kabar yang akhirnya disepakati untuk minum jus bersama di kantin sekolah.
“Emang enak sih, bisa mengurus anak sendiri, mengurus rumah sendiri. Gak usah pusing kayak aku sekarang. Tiap abis Lebaran, pasti masalah pembantu dan suster yang bikin mumet kepala. Terpaksa deh harus cuti, harus ngepel sendiri, nyapu sendiri, jemput anak sendiri. Jadi upik abu deh setahun sekali..” sekali lagi pemilik wajah itu tertawa lepas.
Anganku melayang pada mama yang tinggal berlainan kota denganku. Bekerja adalah hidup buat mama. Hampir separuh usia beliau abdikan dirinya pada departemen milik negara. Kenapa seakan aku menemukan sosok mama pada temanku hari ini. Berlainan denganku, mama adalah seorang wanita pekerja. Dia selalu bangun sebelum subuh jauh sebelum anak dan suaminya bangun. Walau kami punya pembantu, tetap saja mama sibuk menyiapkan sarapan di dapur. Mengaduk susu, mengulek bumbu nasi goreng dan sebagainya. Dan tepat ketika jam besar kami berdentang enam kali, mama langsung pergi membelah keriuhan kota. Ingatanku akan mama adalah saat dimana mama pulang menjelang maghrib dengan beragam tentengan oleh-oleh untuk kami. Dan panggilannya kepadaku ketika menjelang Isya untuk memijit kakinya membuatku rindu harum minyak tawon miliknya.
“ Capek sih kerja kayak gini. Tapi aku gak bakal tahan kalo gak megang duit, Va. Belum lagi membayangkan harus di rumah seharian. Bisa bosen aku !”
Kali ini anganku kembali melayang jauh pada seorang Bi Neng yang sudah puluhan tahun mengabdi sebagai pembantu di rumah mertuaku. Sosok agak pincang yang selalu tersenyum walau ada memar lebam di wajahnya. Satu-satunya alasan ibu mertuaku masih mempekerjakan Bi Neng walau dia sudah tua adalah Siti, anak semata wayang pasangan Bi Neng dan Mang Karja. Siti adalah seorang gadis manis kelas 2 SMA yang sering kumintai bantuan untuk membantuku menjaga Shabrina di rumah ketika aku harus bepergian. Sering ketika dia datang, wajahnya kelabu. Dan tanpa penjelasan apapun darinya, aku sudah tahu bahwa penyebabnya adalah pertengkaran orang tuanya. Pukulan demi pukulan yang sering dilakukan oleh Mang Karja yang penjudi itu kepada istrinya-lah yang kupikir membuat Siti menjadi anak pendiam dan tertutup.
“Padahal kamu kan dokter gigi, Va. Gak pengen tuh praktek?. Aku ada temen loh yang punya klinik gigi. Mungkin kamu bisa kurekomendasikan untuk praktek disana”
Aku hanya bisa tersenyum sambil menghirup jus jeruk di depanku. Tak sengaja kulihat kening mulusnya berkerut dan sambil mendecak-decakkan mulutnya dia geleng-gelengkan kepalanya.
“Kan enak, Va, bisa Bantu-bantu suami. Bener deh kalo aku gak kerja mungkin sampe sekarang kami belum bisa punya rumah”
Sembari memainkan jari, kembali lagi pikiranku melayang. Kali ini tertambat pada momen romantis enam tahun lalu; “lamaran koboy” ala Rais yang kini jadi suamiku. Pagi masih dingin sekali di kaki gunung Halimun, ketika serombongan pencinta alam dari Universitas Indonesia bersiap berangkat menempuh perjalanan mendaki gunung berkabut itu. Aku yang baru saja dilantik sebulan lalu menjadi anggota kelompok ini masih gelagapan membenahi bawaanku. Ketika nyaris saja aku menjatuhkan carierku karena salah posisi, tak disangka sepasang tangan menahannya dan si pemilik tangan langsung menyambungnya dengan pertanyaan: “Maukah kamu jadi ibu buat anak-anakku?”. Walau kami berjalan menembus kabut tapi tak pernah kurasakan pagi sehangat hari itu dalam hidupku. Enam bulan kemudian kuputuskan untuk mengikatkan diriku selama-lamanya dalam pernikahan kami.
“Bisa aja sih aku berhenti kerja sekarang. Tapi kayaknya gaji suamiku gak bakal cukup deh untuk kebutuhan sehari-hari. Apa-apa kan mahal sekarang.”
Tak terasa mataku menajam memperhatikan gerombolan murid-murid SMA yang sedang asyik ngobrol sambil bertukar lagu dengan HP- nya. Aku jadi terkenang pada Emak; nenekku yang masih terus memanjakanku walau aku sudah SMA. Bertolak belakang dengan mama, Emak -yang adalah ibunya- adalah seorang guru Sekolah Rakyat (setara SD di zaman Belanda) yang akhirnya memutuskan untuk berhenti mengajar ketika anak bungsunya lahir. Pernah dulu aku sering tak habis pikir, bagaimana bisa Emak yang tidak berpendidikan tinggi bisa mengantar ketujuh anaknya -empat laki-laki dan tiga perempuan- menjadi sarjana semua. Kalau kutanyakan hal itu, tak ada satupun jawaban terlontar dari mulut Emak kecuali tangannya yang langsung mendekapku dalam pelukannya yang seakan tak berujung. Sedangkan Abak -kakekku- adalah seorang mantan pejuang yang tidak pernah mau tahu “urusan perempuan”. Badannya yang masih tegap sampai sekarang, masih kuat digunakan mengayuh sepeda tiap pagi. Untuk cucu-cucunya, Abak bukanlah tempat bermanja walau terkadang sering kulihat dia termenung-menung memandangi album foto keluarga besar kami.
“Ah, kalau saja kita yang perempuan-perempuan ini tidak harus dibebani sekian banyak tanggung jawab, mungkin kita bisa jadi diri sendiri, ya Va. Enggak harus dibebani kerja, anak, suami atau rumah. Menurut kamu gimana, Va?”
Krriiiiiiiiiiiing…………Deringan bel panjang membuatku tidak bisa menjawab pertanyaan pertama darinya buatku di obrolan panjang kami siang ini. Dan ketika aku berbalik dari tempat duduk, kulihat seorang anak keriting berkuncir dua mengembangkan tangannya sekaligus tak lupa berteriak keras “Bundaa…….”
Sambil kugandeng tangan kecilnya, kujawab dalam hati pertanyaan temanku tadi bahwa menjadi siapapun tidak menjadi soal buat seorang perempuan. Yang penting adalah bagaimana kita akhirnya bisa bahagia dengan pilihan kita, bisa tersenyum ketika menjalani konsekwensinya dan bisa bersyukur ketika menyelesaikannya. Aku belajar banyak dari Mama, Bi Neng, Emak, bahkan dari diriku sendiri.
Labels: tentang diri-ku




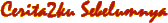




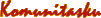
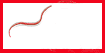




0 Comments:
Post a Comment
<< Home