 (foto Shabrina bersama Nenek Surti) Kalau saja aku bisa memutar waktu, malas rasanya berada disini. Diantara kerumunan Om, Tante, Uwak dan Mamak yang mengobrol riuh sambil tertawa-tawa. Entah apa yang mereka perbincangkan sampai harus mengorbankan telinga orang-orang di sekelilingnya.
(foto Shabrina bersama Nenek Surti) Kalau saja aku bisa memutar waktu, malas rasanya berada disini. Diantara kerumunan Om, Tante, Uwak dan Mamak yang mengobrol riuh sambil tertawa-tawa. Entah apa yang mereka perbincangkan sampai harus mengorbankan telinga orang-orang di sekelilingnya. “Nah, ini dia Eva betino kito. Ngapo belum nambah anak hah?..”
Itu lagi itu lagi pertanyaan yang harus kuhadapi setiap aku bertemu salah satu dari mereka. Sedangkan suamiku dengan santainya duduk bersila diatas tikar sambil tersenyum-senyum melihat kusutnya mukaku.
“Tambah lah anak tu. Jangan lamo-lamo. Dak takut kalo ketuoan hah?”
“Insya Allah, Wak”. Yah, hanya itu jawaban standar yang terlontar dari mulutku. Mau gimana lagi, pahit mulut ini menjelaskan alasanku kepada mereka juga tak bakal mendapat tanggapan yang konstruktif.
Tau gak sih susahnya mengurus anak itu?, gerutuku dalam hati. Tanpa sadar kuperhatikan satu persatu orang-orang tua yang duduk didepanku. Tante Sumi adalah keponakan Mamaku yang paling besar. Rambutnya yang hitam masih tergelung rapi, khas wanita seberang. Anaknya ada tujuh orang dan semuanya laki-laki. Ya, Tuhan, tanpa sengaja aku berucap sambil membayangkan repotnya dia setiap hari. Om Irwan, sepeninggal istrinya karena kanker delapan tahun lalu dia menikah lagi, dan total jumlah anaknya dari istri pertama dan kedua adalah sepuluh orang. Wah, padahal si Om hanyalah guru PNS biasa. Bagaimana ya dia harus menyekolahkan sepuluh anaknya?.
Di pinggir tembok menyandar pada pilar ada Kakek Imron. Beliau masih terhitung sepupu Kakekku. Tapi dibanding dengan Kakek yang sudah mulai pikun sekarang, Kakek Im - begitu kami biasa menyapanya- masih segar bugar. Mulutnya masih sibuk mencangklong pipa hitamnya. Yang ini pun sami mawon, dengan dua istri yang dinikahinya dia mendapat delapan orang anak. Bahkan anaknya yang terkecil masih seumuran denganku.
“Banyak anak tu banyak rezeki, Va. Nah, liat lah Uwak-mu ini tak pernah habis harta karena dua belas anak” yang ini adalah komentar Wak Nasim si saudagar sepatu. Terang saja dia enteng berucap seperti itu, toko sepatunya menyebar di tiap mall yang ada di Jakarta ini. Itu mah gak fair,Wak. Tapi kalau kulancarkan protesku, dia hanya tertawa terbahak-bahak sampai matanya berlinang air mata.
Menjadi seorang ibu adalah pengalaman paling ajaib yang pernah terjadi pada diriku. Setelah sepuluh bulan setengah janin-ku belum lahir juga, dokter kandunganku akhirnya memutuskan untuk “memaksanya” keluar. Operasi caesarku enam tahun lalu adalah operasi pertama buatku. Seumur hidup belum pernah aku masuk ke kamar operasi. Tak sampai 30 menit, lahirlah Shabrina bidadari kecilku dengan tangisan keras seakan protes karena “dipaksa” melihat dunia. Tak pernah kubayangkan bayi kecil itu ternyata langsung mengubah Eva 180 derajat. Melihat bayi itu tidur dalam pelukan membuat diri ini tidak berarti apa-apa tanpa dirinya. Hilang sudah egois-ku, kekanakan-ku, harga diriku, yang ada hanya dia. Tertatih sebagai ibu baru, aku belajar mengasuhnya sendiri. Kususui dia dengan harapan besar, kuayun dia dengan cita yang tinggi dan kubelai dia dengan kasih abadi. Berpisah dengannya bisa membuatku gelisah bukan kepalang. Apalagi setiap pagi menjelang, ketika aku terpaksa meninggalkannya pada Neneknya. Kuliahku yang tinggal menjalani kerja praktek di rumah sakit mengharuskanku berpisah dengannya selama delapan jam setiap hari, tapi sungguh itu seperti seabad lamanya. Dan tangisanku –lah yang menjadikan seakan malam-malam begitu kelam ketika dia jatuh sakit.
Semua momen itu masih terbayang jelas di mataku. Bahkan masih bisa kurasakan sakitnya puting susuku yang lecet berat ketika menyusui anakku. Semua masih jelas terasa. Kesibukanku makin bertambah ketika dia mulai “sekolah”. Karena ikutan tren, aku memasukkannya ke sebuah sekolah ala bermain saat Shabrina berumur 2 tahun. Saat itu aku ikutan berlari ketika dia berlari, ikut melompat ketika dia melompat, ikut bernyanyi “the itsy bitsy spider” lengkap dengan gerakan tangannya. Dia ikut kelas toddler, akupun ikut ngintil sebagai toddler juga. Kuat gak ya aku mengulangi semua kejadian itu?. Apakah masih ada sisa tenaga untuk adiknya nanti?. Pertanyaan itu yang terus menggaung saat aku mencoba menelisik kesanggupan diri untuk hamil lagi.
Mataku kembali melirik kumpulan orang yang sedang duduk di depanku, tapi sekarang fokusnya berpindah pada kumpulan “generasi muda”-nya. Kebanyakan dari kami mempunyai lebih dari 4 orang saudara kandung. Suku kami memang mengagungkan anak. Bagi suku kami, anak adalah harta terbesar dan berguna untuk menjaga kelangsungan budaya.
Sekilas kuingat, bagaimana Mama harus susah payah bekerja membanting tulang ikut membantu Papa bekerja siang malam demi untuk menghidupi kami tujuh bersaudara. Tak jarang kulihat Mama terpaksa meloloskan gelangnya ke toko emas untuk biaya kuliah kami. Kuingat juga Mama yang terkantuk-kantuk menunggui kakak belajar sampai jauh malam, Papa yang begitu sabar melerai pertengkaran kami, dan sempitnya kamar-kamar tidur kami yang terpaksa harus dihuni oleh 3 orang didalamnya. Tapi, benar, aku tidak pernah melihat Papa atau Mama kesusahan karena tingkah kami. Selalu mereka bersikap apa adanya seperti layaknya orang tua. Mereka marah kalau kami salah, mereka menangis kalau kami kecewakan dan mereka bahagia saat kami senang. Tak ada tuntutan atau permintaan balasan pada kami.
“Tiap anak itu ada pintu rezekinya, Va” terngiang kembali kata-kata Mama ketika kami sedang mengalami kesulitan keuangan karena di PHK-nya Papa. Mama percaya itu bahkan beliau sering mengatakan bahwa dia sudah membuktikannya. “Kau mesti percaya bahwa ada tiga hal yang pasti akan selalu ada rezekinya dari Tuhan. Untuk menyekolahkan anak kita, untuk membuatkannya tempat berlindung dan untuk menikahkannya”. Percaya gak percaya, tapi kupikir benar juga isi kalimat tadi.
Mungkin tingkat ketergantungan-ku pada Alloh yang kurang kuat dibandingkan dengan orang-orang tua dulu. Kalau semua sudah disandarkan pada-Nya, maka semua hal menjadi blaur dan tidak terjelaskan. Nilai inilah yang mulai tergeser di zaman materialisme ini. Di zaman yang semuanya diukur lewat materi dan tampilan fisik.
Kekhawatiran tidak bisa menyekolahkan anak, tidak bisa memberikannya rumah yang terbaik, tidak bisa memberikannya susu dan makanan yang terbaik, itulah sebenarnya awal semua ini. Tapi bukan berarti dulu orang-orang tua kita tidak punya kekhawatiran seperti ini juga. Mereka pun mempunyai kekhawatiran yang sama. Tapi mengapa mereka seakan tidak tergoyahkan?. Bukankah selama ini mereka - orang-orang tua kita – juga sudah memberikan yang terbaik buat kita ? Pendidikan terbaik, rumah terbaik bahkan makanan terbaik. Kemudian apa yang membedakan kita sekarang dengan mereka dulu?. Zaman-kah yang berubah ?. Tapi haruskah keyakinan bersandar pada-Nya pun harus berubah?
“Tante bunda, kenapa sih rambut Kakek warnanya putih semua?” tau-tau keponakan-ku yang baru berumur lima tahun sudah berada didepanku dengan tampang lucunya. Kupandangi wajah tengilnya. Dan kududukan dia ke pangkuan. Andai saja dia sudah mengerti maka akan kujelaskan panjang lebar bahwa rambut putih Kakeknya adalah bukti kerja keras beliau menghidupi kami semua, anak-anaknya..
Labels: tentang keluarga-ku




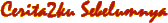




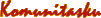
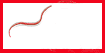




1 Comments:
mba eva, kalau buat saya, masalah mau nambah anak bukan mempersoalkan rezekinya...tapi saya mempersoalkan pengasuhnya :-P kalau anak saya usianya terlalu berdekatan dengan adiknya, artinya saya harus punya dua pengasuh dirumah...nah, zaman sekarang ngurus satu pengasuh aja repot dan ribet, apalagi dua, hehehe...makanya, saya berpikir untuk menjarakkan kehamilan itu dengan mempertimbangkan supaya cukup satu pengasuh dengan dua anak...gitu mba :-D
kecuali kalau tiba-tiba saya diberi kesempatan untuk tinggal dirumah..malah kayaknya gpp deh punya anak banyak dan berdekatan usianya, hehehehe (tentunya tetep pake asisten :-p)
Post a Comment
<< Home