
Bukannya aku tidak mau patuh pada suami. Rasa-rasanya keinginanku saat ini tidak berlebihan. Apakah memang ada perbedaan cara pandang antara laki-laki dan perempuan dalam hal ini?. Pertanyaan tadi yang terus menggangguku, ketika hampir saja terjadi konflik terbuka dengan suami tercintaku. Entah kenapa, kurasakan dia terlalu memaksakan kehendaknya padaku saat ini. Bukankah aku bisa menentukan pilihanku?
Huih, berbeda sekali dengan Rais yang kukenal. Pertama kali kenal dia di kampus kami dulu, Rais adalah cerminan sosok demokratis dan liberal khas anak Fisika. Enak saja dia merancang tugas yang bertentangan dengan aliran sang dosen sehingga nilai D sering dia terima. Tapi tidak pernah tercetus sekalipun pikiran untuk merubah cara pandangnya. Baginya keindahan suatu ilmu adalah di saat dia bisa menuangkan secara total, sekali lagi, secara total ekspresi dirinya. “Dinding” yang mencuat dengan komposisi yang tidak kompromis terhadap aturan baku adalah karya-karya monumentalnya.
Begitu juga di Senat kampus, buatku yang anak kedokteran, sikap Rais yang sering menyederhanakan masalah, hatta itu adalah masalah prinsip, sering tidak masuk akal sehatku. Bagiku kalau yang namanya sudah aturan ya tetap harus ditaati. Tapi bagi Rais, ketua Senatku dulu ini, siapa pun orang yang bisa memberikan ide terbaik untuk memecahkan sebuah masalah maka peraturan orang itu-lah yang akan dipakai. Apa pun caranya. Buat Rais, cara yang paling efektif dan efisien untuk menyelesaikan masalah adalah ketika kita mencoba berdiri diluar jauh dari masalah itu. Termasuk mencoba keluar dari aturan, norma ataupun kepatutan yang biasa dilakukan. Semakin `gila` jalan keluarnya, maka biasanya semakin efektif solusinya.
Tapi sikapnya yang bebas merdeka, yang selalu terbuka pada pendapat orang lain, yang selalu menghargai setiap potensi orang itu-lah yang membuatnya terpilih menjadi ketua Senat selama dua periode. Di bawah kepemimpinannya sudah banyak teman-temanku yang dulu `bukan apa-apa` menjadi mekar berkembang menjadi mahasiswa-mahasiswa yang bisa diperhitungkan kiprahnya. Rais sendiri bukanlah tipe pemimpin yang senang berada di depan. Dia lebih senang kalau kiprahnya tidak terlihat. Begitu ungkapnya dulu padaku yang sering kusambut dengan cibiran bibir.
Masih jelas terbayang ketika kampusku menjadi tuan rumah pendeklarasian satu kesatuan aksi mahasiswa yang cukup berperan tahun 1998. Di saat teman-temannya yang sama-sama penggagas organisasi ini satu persatu diwawancarai koran, majalah dan stasiun TV, Rais dengan santai menggamitku pergi dan membawaku ke toko buku untuk merayakan ulang tahunnya. Padahal dia-lah otak yang merancang struktur organisasi ini sehingga bisa menjadi kesatuan aksi mahasiswa yang memegang puncak komando untuk para mahasiswa di Jawa dalam gelombang reformasi 1998. Boleh dibilang kesatuan aksi ini adalah cikal bakal angkatan 98 yang sekarang pentolannya banyak menjadi petinggi partai dan anggota majelis.
Tak kupungkiri hal-hal itulah yang membuatku jatuh cinta padanya. Sederhana, terbuka, bebas, dan apa adanya, serasa dia bukanlah berasal dari dunia kepalsuan ini. Di dekatnya aku bisa menjadi Eva yang sebenarnya. Bukan Eva yang anak sulung, bukan Eva yang anak kedokteran gigi, bukan Eva yang aktivis mahasiswa . Nyaman sekali berada di sampingnya. Di dekatnya aku bisa menangis panjang karena kesal pada Mama yang selalu memaksakan kehendak, di dekatnya aku bisa melamun menatap tingginya ombak pantai Pangandaran tanpa resah belum belajar untuk kuis esok, di dekatnya bisa kurasakan betapa dia sangat menghargai Eva sebagai seorang manusia. Dengan segala pilihanku dan segala konsekwensi yang bakal kuhadapi nantinya.
Aku belajar banyak darinya. Tapi tidak pernah sekalipun dia berlagak seperti guru di depanku. Dia tetaplah Rais, kekasihku yang menerimaku apa adanya. Bahkan di awal-awal pernikahan kami, ketika aku memutuskan untuk total menjadi seorang ibu rumah tangga. Tidak ada satupun komentar keluar dari mulutnya, hanya senyuman sayang saja yang mengiringi dekapannya.
Sekali lagi kubalik-balik halaman indeks warna di salon muslimah langganan kami ini.
“Jadi gak coloring-nya, Bu?” terhenyak aku mendengar pertanyaannya.
“Nah, warna ini yang lagi ngetrend sekarang, Bu. Hazelnut gelap, cocok deh sama kulit Ibu” katanya dengan suara agak mendesak.
Pagi ini, hari Sabtu yang memang sudah sangat kunantikan sepanjang minggu. Aku dan sahabat akrabku –Dhanti- sudah menyusun janji untuk pergi ke salon langganan kami. Berbeda dengan Dhanti yang mantan cover girl, sudah lama aku tidak ke salon. Hampir tiga bulan. Maklum rambutku yang lurus ini tidak memerlukan perawatan yang rumit. Tinggal dipotong bob pendek, diberi hair tonic tiap malam dan sesekali creambath sendiri di rumah. Tapi hari ini lain. Aku dan Dhanti berencana mengubah warna rambut kami. Pengen variasi dan ganti gaya saja, begitu alasan kami.
Dan semuanya bermula dari pertanyaan suamiku yang dilontarkannya sesaat sebelum aku mengulas sapuan bedak terakhir di wajahku. “Tumben semangat banget. Biasanya kamu paling males nemenin Dhanti ke salon, Va?”. Langsung dengan berapi-api kubeberkan rencana kami untuk mengecat rambut kami. Tak disangka wajahnya berubah menjadi serius dan menohokku dengan kalimat “Aku gak setuju, ah. Aku lebih suka kalo kamu biasa saja, Va”. Tentu saja ini diluar dugaanku. Kalimat “…Aku lebih suka kalo kamu biasa saja” akhirnya menjadi perdebatan kami pagi ini. Menyebalkan, karena kali ini pendapatnya sama sekali tidak logis buatku.
Sudah berulangkali Dhanti meyakinkan sejak tadi, bahwa ini hanya soal warna rambut. “Itu tidak mengubah diri kamu, Va. Kamu tetap Eva, yang istrinya Rais dan bundanya Shabrina. Tidak ada yang berubah. Lagian kamu kan pake jilbab. Gak bakal kentara perubahan warna rambut kamu di mata orang lain” begitu katanya. Tapi benarkah ini tak mengubah diriku?. Benarkah warna rambut tidak penting buatku? Atau memang suami-ku saja yang membesar-besarkan masalah. Kalau memang aku merasa bisa bebas memilih, kenapa kali ini aku merasa bimbang ?. Bukankah ini rambutku, tubuhku? Dan seperti kata Dhanti tadi, aku pun tidak akan berubah hanya gara-gara warna rambutku. Kenapa aku harus begitu peduli pada perasaan suamiku?
“Dhan, aku mau potong rambut dan creambath aja deh” akhirnya keluar juga keputusanku. Dhanti membelalakan matanya sambil tersenyum.
“Aku tahu kamu pasti akan memutuskan itu, Va” lanjutnya tulus.
Kuurai lagi kejadian tadi pagi. Kuhadirkan wajah suami tercintaku. Kucoba untuk memahami perasaannya. Mungkin memang saat inilah aku harus menerima dia apa adanya. Sisi dirinya yang selama ini tidak pernah kuketahui. Mungkin tidak masalah buatnya, bila aku memutuskan total menjadi ibu rumah tangga. Mungkin tidak masalah buatnya, bila aku belum mau memberi adik lagi buat Shabrina. Tapi mengubah warna rambutku adalah masalah besar buatnya. Dan aku akan menerima itu sebagai rasa sayangku padanya. Mencoba untuk menghargai pendapat dan kemauannya. Walau memang terasa agak konyol buatku.
Labels: tentang diri-ku




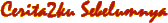




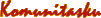
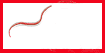




1 Comments:
Hihihi, nurut ya mbak sama suami :)
Post a Comment
<< Home