Suara apa tuh? Dengan antusias aku longokan kepalaku keluar jendela, Loh ada apa rame-rame di sana?. Supaya lebih jelas lagi aku melangkah menuju teras. Kulihat samar-samar di balik rimbunnya daun pohon sekumpulan ibu-ibu yang menggunakan kerudung berbaju rapi duduk melingkar. Dengan seksama kudengarkan kalimat demi kalimat yang keluar dari pengeras suara di seberang. Ternyata Bowo, anak ibu Haji akan menikah pekan depan rupanya. Terus ini acara apa ya?. Kutajamkan lagi mataku untuk melihat lebih jelas. Ada ibu Mar tetangga sebelah rumahku, ada Tante Mirna tetangga sebelah juga, ada ibu ketua cluster, bahkan ada mbak Vivi yang berlainan blok denganku.
Kok aku gak diundang ya? Begitu gumamku sambil melangkah kembali ke dalam rumah. Padahal aku kan cukup dekat dengan bu Haji. Tiap berpapasan, pasti aku menegurnya walau tidak berbincang akrab. Begitu juga dengan Bowo, aku-lah yang memberi informasi tentang lowongan pekerjaan di kantor temanku sehingga dia tidak menganggur lagi.
Baru satu setengah tahun lalu kami pindah ke komplek perumahan di daerah Cibubur ini. Komplek perumahan yang bagus, lingkungannya sudah tertata rapi. Pohon-pohon peneduh jalan juga sudah tumbuh tinggi di sana-sini. Aku-lah yang memutuskan untuk membeli rumah disini karena banyak pilihan sekolah untuk Shabrina di sekitar Cibubur. Tinggal memilih mau ke sekolah yang biayanya murah, menengah atau mahal, semua ada. Hanya uang yang menjadi penentu. Tinggal di sini cukup nyaman. Sistem cluster membuat tidak banyak mobil lalu lalang di jalan depan rumah kami. Sehingga Brina bisa leluasa bermain sepeda atau berlarian sepanjang sore. Dengan tetangga pun kami cukup akrab. Dengan konsep rumah taman yang tak ada pagar antar rumah membuat kami seakan menjadi dekat.
Yah, keputusan membeli rumah ini juga didasari oleh keinginan untuk hidup mandiri di atas kaki sendiri. Sampai lima tahun awal pernikahan, kami masih mengontrak. Kami memang belum sanggup untuk beli rumah sendiri. Dan ketika ada tawaran pinjaman (tanpa bunga) pembelian rumah dari perusahaan suamiku bekerja datang pada kami, tanpa pikir dua kali kami mengambil tawaran itu.
Cukup banyak penyesuaian dan adaptasi yang kulakukan sejak pindah kesini. Aku harus belajar mengatur rumahku sendiri beda dengan di rumah kontrakan dulu yang cenderung semau gue, mulai sedikit-sedikit belajar menata rumah dan belajar memasak. Dan terutama adalah aku harus belajar untuk bersosialisasi dengan tetangga. Untuk aku yang mantan aktivis mahasiswa, dari hari ke hari kegiatanku hanya kampus dan rumah. Sangat jarang aku beramah tamah dengan tetangga. Saling mengunjungi, berbagi makanan, adalah sesuatu yang baru buatku. Sama sekali aku tak mengira bahwa masih ada kepedulian seperti itu di Jakarta.
Tapi aneh memang, di kompleks perumahan ini hal itu masih dijumpai. Ingat sekali, minggu pertama pindah kesini. Kami langsung melapor ke ketua cluster dan tak terlintas pikiran untuk mengenalkan diri pada tetangga sekitar rumah. Tak disangka malamnya serombongan ibu dan bapak mengetuk pintu rumah kami, dengan senyum lebar mereka memperkenalkan diri mereka satu persatu lengkap dengan nama anak-anaknya. Wah, sungguh kejutan buat kami. Apalagi rata-rata ibu dan bapak tadi sudah lebih tua dari kami. Apakah kami yang lebih muda ini kurang bisa berbasa-basi? Ataukah ini yang namanya tidak tahu tata krama? Tak tahulah.
Sejak saat itu aku mulai belajar menjadi tetangga yang baik. Mulai ikutan arisan cluster dan senam taichi bersama tiap hari minggu di lapangan komplek. Suamiku-Rais- juga mulai ikutan klub mancing bapak-bapak. Tapi kami akui sering kami lakukan hal ini dengan terpaksa. Cuma memenuhi kewajiban. Tidak enak kalau tidak datang. Terus terang kami lebih nyaman bersantai di rumah bila ada waktu luang. Mengobrol bertiga di dalam kamar, Bercanda segala hal, dan baru mandi menjelang sore adalah acara favorit keluarga kami di akhir pekan. Kebetulan aku dan Rais memang tipe anak rumahan sejak kecil – setidaknya begitu kata Mama-mama kami. Ari-arinya dikubur di rumah sih, coba dilarung di laut begitu kata mereka.
Kembali aku berjalan menuju teras. Sambil pura-pura menyiram tanaman kuamati lagi kegiatan di rumah tetanggaku itu. Oh, sedang shalawatan rupanya. Pelan kusenandungkan shalawat berbarengan dengan suara dari seberang. Kembali aku menerawang jauh teringat pada masa-masa gadisku sebelum menikah. Dulu di tahun 1998 ketika perekonomian kita runtuh karena krisis ekonomi, aku pernah aktif di sebuah LSM yang bergerak di Cilincing. Di LSM yang kudirikan bersama teman-teman seangkatanku, aku berada di divisi pendidikan. Program kami adalah menjalankan les matematika dan bahasa Inggris gratis buat anak-anak nelayan di Cilincing. Seminggu dua kali dari kampus Salemba kami beramai-ramai naik bis menuju terminal Tanjung Priok dan disambung lagi dengan naik angkot merah jurusan Cilincing. Perkampungan nelayan disana mayoritas dihuni oleh orang Madura. Untuk mendapatkan kepercayaan mereka, kami sempat dua bulan bolak-balik kesana tanpa melakukan apa-apa. Yang kami lakukan hanya duduk-duduk sambil mengobrol dengan sesepuh mereka di rumahnya. Saat itu benar-benar kurasakan kami berenam hampir saja menjadi orang Madura dengan segala tindak tanduk mereka. Canda khas mereka, logat bicara mereka bahkan sampai makanan kesukaan mereka sempat menjadi bagian hidup kami. Kami seakan menyatu dengan mereka. Pernah menjelang hari Raya kurban, LSM kami dimintai bantuan oleh masyarakat disana untuk mempersiapkan pemotongan hewan kurban. Karena acaranya besok pagi-pagi sekali, kami terpaksa menginap di sana. Di rumah salah seorang tokoh masyarakat, kami tidur hanya diatas tikar tanpa bantal. Malam itu sepicing matapun kami tidak tidur karena sibuk mengusir nyamuk laut yang terkenal galak.
Berbeda dengan sekarang, terutama aku, aku tidak merasa menyatu dengan orang-orang di kompleks ini. Lucu saja rasanya harus setor muka tiap sore mengobrol berbasa-basi dengan para ibu di depan jalan. Bukan apa-apa. Aku pikir obrolan sore itu hanya buang waktu saja, kalau tidak gossip ya ngomongin orang. Jadi-lah aku sering berada di dalam rumah sepanjang sore. Kalau tidak di depan PC, aku akan membaca satu buku yang tertunda. Tapi berbeda dengan Brina, dia punya banyak teman kecil di sekitar rumah sekarang. Dari balik jendela biasanya kuperhatikan dia yang sedang bermain dengan anak tetangga. Wah, aku kalah ngetop dengan Brina di sini. Ibu-ibu di cluster ini lebih mengenalku sebagai Bunda-nya Brina dibanding sebagai Bu Eva. Pernah ketika sedang lari pagi ke danau bersama aku dan ayahnya, tiba-tiba Brina menyalami tangan seorang nenek yang berpapasan dengan kami. Padahal aku tahu persis, dia bukan penghuni blok kami. Tentu saja kami bengong melihat tingkahnya, tapi sang nenek tidak marah malah tersenyum senang. Selidik punya selidik dengan bertanya-tanya pada pembantuku, ternyata itu adalah eyang-nya Zahra – rumahnya beda tiga rumah dari kami- yang sebulan sekali datang dari Semarang dan menginap di rumahnya. Ternyata `ketenaran` anakku sudah melintasi propinsi.
Mungkin aku memang tidak harus bertanya-tanya ataupun tersinggung karena tidak diundangnya aku ke selametan di seberang. Malah aku seharusnya lebih bisa mengintropeksi diri. Karena seperti kata Emak -nenekku, orang lain itu adalah cermin buat kita. Begitulah kita, maka begitulah orang lain kepada kita. Mungkin aku memang harus belajar ikhlas dan tulus dalam segala hal seperti tulusnya seorang anak, seperti Shabrina. Apalagi pada tetangga, saudara kita yang paling dekat.
Labels: tentang keluarga-ku




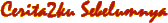




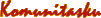
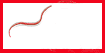




0 Comments:
Post a Comment
<< Home