Ada harga yang harus dibayar untuk segala hal. Bukan selalu uang untuk membayarnya. Bisa waktu, tenaga, perasaan, perhatian, dan cinta. Memang tidak ada yang gratis di dunia ini. Tapi benarkah?
“Bisa kan Va ?, Cuma dua hari satu malam kok “ adikku bertanya di telepon sore itu. Nadanya setengah memaksa. Mau bagaimana lagi?. Tak mungkin aku menolak, dia adalah adik kandungku dan anak-anaknya adalah keponakanku.
“Ok deh. Jam berapa kamu antar Kiki dan Kaka ?” tanyaku menyerah.
“Pokoknya besok pagi-pagi banget aku sudah ada depan rumahmu. Ya ?” sekali lagi dia menegaskan. Tak ada lagi yang bisa kulakukan.
Sudah puluhan kali kejadian ini berulang. Berawal ketika adikku, dan suaminya, setahun lalu meninggalkan rumah orang tua kami dan membeli rumah sendiri. Akhirnya mereka dapat mandiri setelah menumpang di pondok mertua indah selama 4 tahun umur pernikahan mereka. Dia, adalah adik pas dibawahku. Boleh dibilang kami berdua lumayan akrab sejak kecil. Tapi kebalikan denganku dia adalah wanita karier yang cukup hebat di usianya yang baru 30 tahun. Sekarang dia adalah pemilik jaringan klinik.
“Kenapa lagi, Jeng?. Mau nitipin Kiki dan Kaka lagi?.” Suara suamiku mengagetkanku. Seperti biasa dia berkata dengan nada kalem tanpa ekspresi.
“Iya. Ayah gak keberatan kan?” cuma anggukan kepala kuterima darinya. Itulah suamiku, dia cukup mengerti kalau ini adalah masalah sensitif buatku.
Memang mengherankan, tapi adikku yang satu ini sama sekali tidak percaya pada pembantu dan baby sitter yang menjaga kedua anaknya. Setiap kali dia harus pergi keluar kota untuk bertugas, pasti dia akan menitipkan kedua anaknya ke rumahku. Padahal ada suaminya yang sudah pasti akan ikut mengawasi anak-anak mereka, tapi tetap saja dia tidak percaya. “Aku pengen benar-benar ada orang yang aku percayai untuk menjaga anak-anak. Ya kamu-lah itu, Va”, katanya. Apakah itu berarti dia tidak mempercayai suaminya yang sekaligus ayah kedua anak mereka? Hehehe....
Ada harganya untuk semua yang sudah dia dapatkan. Dibandingkan dengan kami, adikku dan suaminya sudah jauh melampaui kami dalam hal materi. Suaminya bekerja sebagai seorang konsultan IT untuk sebuah perusahaan di London, dan adikku adalah seorang dokter gigi muda yang pasiennya antri dimana-mana. Banyak materi yang mereka miliki belum kami miliki.
Terkadang aku berpikir positif menghadapi sikapnya mungkin untuk orang yang biasa memegang kendali di tempat kerjanya, bukanlah sesuatu yang menyenangkan ketika dia harus kehilangan kontrol walau sebentar saja pada anak-anaknya sewaktu dia sedang keluar kota. Hal ini yang menyebabkan dia harus menitipkan anak-anaknya pada aku, kakaknya, yang pasti bisa berada di bawah kontrolnya, di bawah kendalinya. Yah, walau kendalinya itu harus merepotkan keluargaku, harus membuat kedua anaknya- yang baru berumur 3 tahun dan 10 bulan- boyongan besar-besaran ke rumah uwaknya, harus membuat suaminya mampir ke rumahku dulu setiap hari sebelum pulang kerumah sendiri demi melepas kangen pada anak-anaknya.
Banyak orang yang harus berkorban demi kendali dirinya. Bolehkah kukatakan itu sebagai “berkorban” ?. Bukankah seharusnya adikku-lah yang berkorban untuk pilihan hidupnya ? Kenapa yang berkorban harus aku, anak-anaknya dan suaminya? Kenapa bukan dia?
Begitu pula aku. Ada harga untuk setiap pilihan yang sudah kulakukan selama ini. Misalnya ketika aku memutuskan total menjadi ibu rumah tangga . Tidak dapat kubayangkan seandainya aku harus bekerja full time, tidak bisa mengantar Brina sekolah, tidak mendapatkan pelukannya menjelang tidur siang, tidak bisa memandanginya ketika dia tertidur, tidak bisa menemaninya belajar, entah jadi apa diriku bila kehilangan semuanya. Dan bagaimana dengan rumahku, siapa yang akan memasak, menata koleksi tanamanku, menyiapkan keperluan suamiku dan semuanya? Bahkan untuk membayangkannya saja aku tak berani.
Bukan itu saja, keputusanku untuk menjadi ibu rumah tangga saja juga sering dikritik oleh teman-temanku, dianalisa oleh mama dan menjadi bahan sindiran adik-adikku. Karena bertentangan dengan kultur keluarga besarku yang sebagian besar perempuannya ikut membantu mencari nafkah. Keputusanku ini juga membuatku harus belajar menata ulang konsep diriku tentang uang. Ketika gadis, Eva yang sudah bekerja walau masih kuliah bisa dengan bebas berbelanja dengan uangnya sendiri. Tapi sekarang uang yang ada di tanganku setiap bulan adalah uang suamiku, walau suamiku tidak pernah mengekang keinginanku tapi aku mesti tahu diri. Bukan, ini tidak berarti aku menjadi kurang berdaya dalam menjalani hidup dan menentukan keinginanku, sekali lagi, ini cuma masalah uang dan bukan hidup.
Sering kita kira, uanglah yang akan menjadi kunci penyelesaian buat masalah-masalah kita. Sehingga kita terkadang tidak sungkan untuk membayar terlalu mahal untuk yang namanya materi. Kalau kita memang mencari kebahagiaan, ketenangan dan kelengkapan hidup, kupikir terlalu naïf kalau jawabannya adalah uang. Kesimpulan ini-lah yang membuatku memutuskan untuk tidak bekerja diluar rumah. Atau memang seperti yang kukatakan tadi, aku terlalu takut untuk membayar harganya ?. Atau memang ini hanyalah masalah prioritas ?. Mungkin memang aku dan suamiku yang tidak menempatkan materi pada prioritas pertama. Ataukah kami suami istri adalah orang yang mudah puas dengan keadaan materi kami ?.
Tapi seperti adikku, dia bekerja bukan untuk semata uang. Setidaknya itu pengakuannya. Dia lebih mengutamakan eksistensi diri, penerapan ilmu dan aktualisasi pribadi diatas materi. Dan memang tidak semua orang bekerja untuk uang. Tapi entah kenapa, aku merasa masih terlalu mahal untuk membayar itu semua bila harus mengorbankan keluargaku, rumah tanggaku.
Aku merasa bisa mendapatkan itu semua di rumah bersama anak dan suamiku. Di rumahku aku adalah ratu rumah tangga, aku yang mengambil semua keputusan yang berkaitan dengan keluargaku, aku adalah bunda-nya Brina tempat dia memanggil bila butuh, tempat dia memeluk bila dia sakit dan tempat dia mengadu bila kecewa. Sepertinya sudah lengkap eksistensi dan aktualisasi diriku di rumah. Tak perlu aku mencarinya diluar rumah.
“Tidak masalah kamu mau jadi apa. Yang penting adalah bagaimana kamu menjalaninya” Itulah kalimat yang sering kukatakan pada Brina ketika dia meminta pertimbangan tentang sesuatu. Yang ingin aku tanamkan pada anakku sejak kecil bahwa setiap tindakan, perbuatan dan keputusan dalam hidup ada konsekwensinya, ada harganya. Yang perlu dipikirkan bagaimana kita bisa membayar harga itu. Apakah kita bersedia membayar harga itu dengan rentetan konsekwensi di belakangnya. Berapapun harga dan konsekwensi yang harus kita jalani bukanlah masalah. Karena tidak ada istilah salah dan benar dalam hal ini.
Seperti aku pun, aku tidak pernah beranggapan bahwa adikku salah karena sudah membayar terlalu mahal untuk pilihan hidupnya dibandingkan denganku. Tapi aku hanya yakin bahwa aku lebih merasa cocok dengan harga yang kubayarkan sekarang. Jadi tanpa menawar dan tanpa berpikir dua kali aku menjalaninya dengan hati lapang.


Name: evarais
seorang perempuan 30 tahun-an, seorang ibu, seorang istri. Dengan hidupnya yang penuh warna dalam "perjalanan cinta"-nya....

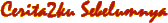
- Blog Pribadi
- Miss Anything
- Ilusi Uang
- Cemburunya Aku ....
- Tetangga depan belakang, kanan kiri
- Anak-anak
- Bangkrut !
- Obrolan kemarin malam
- Bisnisku, Cintaku
- Buat Seorang Pria





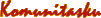
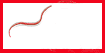




2 Comments:
Lagi2 tulisannya keren banget mba.
Inspirasi buat saya dan pembaca ..
Klo saya setuju dengan pilihan hidup mba, dan saya pun kalau nanti menikah akan mencari perempuan yang siap untuk dirumah (insya allah).
Gpp bekerja dulu, tapi mesti siap untuk keluar nantinya bila diminta. Karena fitrahnya wanita itu di rumah.
Biarlah kami laki-laki yang berkubang debu jalanan :)
Kok aku mau nangis bacanya,hufff..
Disini dikantor ini,aku berjibaku dgn kerjaan penuh target..dirumah memang ada nenek n pengasuh,tapi aku selalu saja ga tentrem..banyak momen yang hilang,dan semestinya itu memang konsekuensi dr yang kupilih..sampai kini aku belum juga seteguh mbak dlm menentukan jln karier,banyak faktor dan pertimbangan.
Post a Comment
<< Home