Siang cukup panas. Berkali-kali kulap titik keringat di dahiku. Tempat kursus melukis ini pun sepi sekali. Tumben, biasanya banyak ibu-ibu yang menunggui anaknya. Mungkin karena panasnya hari membuat mereka merasa lebih betah dirumah. Kusimak sekali lagi lembaran neraca keuangan di depanku.
“Gimana, Va, tahun ini aku sudah untung kan?” tanya mbak Silvi sekali lagi. Mbak yang masih awet muda ini adalah mama dari Reza teman sekelas kursus Shabrina.
“Emang sih ada selisih besar antara pemasukan dan pengeluaran. Tapi ini bukan laba ya,mbak. Karena belum ada aspek penyusutan barang dalam neraca ini.”
“Loh, bukannya itu masuknya di laporan per-tahun, Va?. Ini kan laporan per-bulan”.
“Ya. Tapi akhir bulan ini mbak Silvi akan membuat neraca tahunan kan?. Disaat itulah kita baru bisa menentukan jumlah laba yang sebenarnya. Itu pun kalau mbak tidak ada hutang atau kewajiban yang harus dibayar akhir tahun ini. Sewa ruko misalnya”
“Aduuh, Va. Kamu ini dokter gigi atau akuntan sih?. Kok bisa segitu detil melihatnya”
“Idiih mbak Silvi, ini mah akuntansi sederhana. Anak SMEA aja ngerti kok. Kesalahan kita adalah terlalu cepat ingin memetik untung, tanpa sadar bahwa belum semua aspek pengeluaran kita tulis.”
Tak sengaja kulihat sesosok ibu muda berbaju kuning melenggang kearahku. Wah, ini dia `Miss Anything`. Benar saja, dengan suara yang sok akrab dia langsung menyapaku. Gawat nih, pikirku.
“Eva, mbak Silvi, apa kabar?. Kok kemarin gak datang pengajian sih?. Seru loh materinya.” Mba Desi namanya. Agak lebih tua dariku. Aktivis masjid komplek-ku ini memang selalu ramah. Tapi banyak orang beranggapan sikap ramahnya itu ada maunya. Ada udang di balik batu. Karena setiap dia selesai beramah tamah dengan kita , pasti dia akan menyodorkan barang dagangannya. Mulai dari baju anak-anak, kue-kue, parfum, kosmetik sampai kain songket. Semua ada, segala ada, oleh karena itulah ibu-ibu menjulukinya Miss Anything.
“Aku nemenin ayahnya Reza ke rumah sakit, check up pasca stroke” Mba Silvi menjawab tanpa menoleh dari buku besarnya.
“Eh, apa tuh mba?. Laporan Keuangan Salon ya?” kulihat mba Desi langsung duduk disamping mba Silvi. Mba Silvi memang sudah terkenal sebagai juragan salon. Maklum tiga buah salonnya biasa menjadi langganan kami, ibu-ibu orang tua murid.
“Iya. Biasa deh konsultasi sama Eva. Kecil-kecil gitu Eva kan biasa ngurusin bisnis suaminya”. Aku hanya tersenyum mendengarnya. Dibanding mayoritas ibu-ibu di lingkungan pergaulanku, aku memang termasuk paling muda.
“Sebenarnya lebih enak kalau mba Silvi pakai program akuntansi. Gampang deh mba, tinggal masukin data kita udah langsung tahu keadaan keuangan kita. Adikku yang punya bengkel juga menerapkannya. Sekarang bengkelnya berkembang pesat, karena dia tidak harus direpotkan dengan urusan keuangan” cerocos mba Desi. Mulai nih, dia melancarkan jurus dagangannya. Aku pun menunggu jurus berikutnya.
“O ya ?. Kok bisa? “ tanya mba Silvi datar. Buatku yang cukup akrab dengannya, bisa kulihat sedikit perubahan bahasa tubuhnya menjadi agak waspada.
“Sekarang kan zamannya tekhnologi canggih, mba. Tekhnologi memudahkan kerja kita.” Mba Dewi mulai lagi. “Tanya deh sama Eva yang punya warnet. Berapa ribu informasi terbaru berseliweran di internet tiap hari. Iya kan Va?” Aku cuma mengangguk sambil mengerling jauh.
“Gitu ya?” mba Silvi masih datar bertanya.
“Nah, mangkanya sekarang aku kasih tahu mba Silvi. Kebetulan adik iparku yang bekerja di Bogasari kerja di bagian computer. Dia biasa bikin program computer kayak gitu” Betul kan dugaanku. Pasti ujungnya dagang.
Perkenalanku dengan mba Dewi terjadi ketika aku baru saja pindah ke komplek perumahan ini. Aku yang memang senang berteman, sangat antusias mendengarkan ceritanya tentang suasana komplek ini beserta segala info yang berguna buatku. Karena sudah hampir lima tahun tinggal di Kota Wisata ini, dia tahu bagus-jeleknya komplek perumahan ini, pokoknya lengkap. Banyak info berguna bagiku yang kudapat darinya. Misalnya seperti jadwal pengajian di masjid komplek, telpon pengaduan gangguan Telkom, restoran dan tempat-tempat enak untuk nongkrong di sini dan lain-lain.
Tapi pada pertemuan kedua, barulah ketahuan belangnya. Kenapa kusebut belang, karena menurutku berteman haruslah didasari sikap tulus tanpa pamrih. Baagaimana aku bisa menolak, ketika tiba-tiba dia menyodorkan seperangkat mukenah dagangannya padahal di lain pihak sudah berjam-jam aku mendengarkan `info berguna` darinya. Apalagi ketika dia mengatakan bahwa dia sengaja menemuiku saat itu untuk memberitahuku info penting tentang penjualan kios di Fresh Market yang sedang dibangun. Bagaimana aku bisa menolak?. Padahal masih ada 2 set mukenah baru pemberian mama dan mertuaku yang belum sempat terpakai dalam lemari.
Sejak saat itu aku mulai mewaspadai kehadirannya. Bukan apa-apa, mahal ternyata harga untuk berteman dengannya. Tapi bukan aku saja. Kebanyakan ibu-ibu di sini tampaknya juga terhinggapi sindrom Miss Anything. Ini memang hanya dugaanku. Karena tak jarang kuperhatikan satu persatu ibu-ibu mengundurkan diri dari `kancah` obrolan ketika mba Dewi datang. Daripada dipaksa mending lari duluan, kata mereka.
“Gimana mba Silvi?. Kalau memang berminat, nanti sore kusuruh adik iparku menghubungi mba Silvi” mba Dewi berkata antusias. Kulihat mata mba Silvi menatapku minta bantuan.
“Kalo konsultasi awal gak perlu bayar kok, mba. Cukup mba Silvi kasih tahu kebutuhan mba nanti adik iparku bikin usulan proposal ke mba” Sekali lagi Miss Anything melancarkan jurus mautnya. Coba dulu baru bayar. Itulah moto dagangnya yang sangat sulit ditolak. Akhirnya dengan beribu macam alasan kami berhasil melepaskan diri dari Miss Anything, walau harus dengan sedikit berbohong.
Apakah harus bermuka badak seperti itu untuk berdagang? Dalam setiap kesempatan menawarkan dagangan walau harus memanfaatkan perasaan orang lain ?. Aku pun berdagang. Tapi buatku tidak harus membuat orang sungkan untuk bilang `tidak` disaat memang dia tidak memerlukan barang itu. Aku berusaha untuk menjadi pedagang yang ber-etika, berusaha untuk tidak memanfaatkan perasaan sungkan orang untuk menolak kita. Aku belajar banyak pada bapak mertuaku. Beliau adalah pedagang tulen sejak kecil. Tamat SMA dia langsung merantau ke Jakarta, dan langsung memulai usaha pertamanya yaitu berdagang baju di kaki lima. Hingga sekarang dia mempunyai beberapa toko baju di Tanah Abang. Tapi sekalipun dia tidak pernah memaksa orang untuk membeli dagangannya. Selalu ada proses tawar menawar sebelum itu. Kalau terjadi kesepakatan maka selesailah proses jual beli itu tapi bila tidak bukan menjadi masalah bila harus batal. Prinsip berdagang adalah ketika penjual dan pembeli bisa sama-sama senang dan puas, begitu nasehatnya setiap dia bercerita tentang kiatnya berdagang. Tidak boleh ada yang merasa terpaksa harus menjual ataupun tidak boleh ada juga yang merasa harus membeli.
Semua orang butuh uang, aku pun tahu itu. Tapi tidak langsung menjadikan kita selalu bertindak berdasar uang. Tapi menurutku sebenarnya hal ini berlaku untuk semua hal, bukan hanya dalam berdagang.


Name: evarais
seorang perempuan 30 tahun-an, seorang ibu, seorang istri. Dengan hidupnya yang penuh warna dalam "perjalanan cinta"-nya....

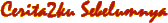
- Ilusi Uang
- Cemburunya Aku ....
- Tetangga depan belakang, kanan kiri
- Anak-anak
- Bangkrut !
- Obrolan kemarin malam
- Bisnisku, Cintaku
- Buat Seorang Pria
- Ayah Botak !
- Pohon Petai Cina





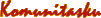
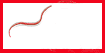




0 Comments:
Post a Comment
<< Home